Catatan Refleksi Akhir Tahun Sekolah AMAN. oleh: Ima Gita.
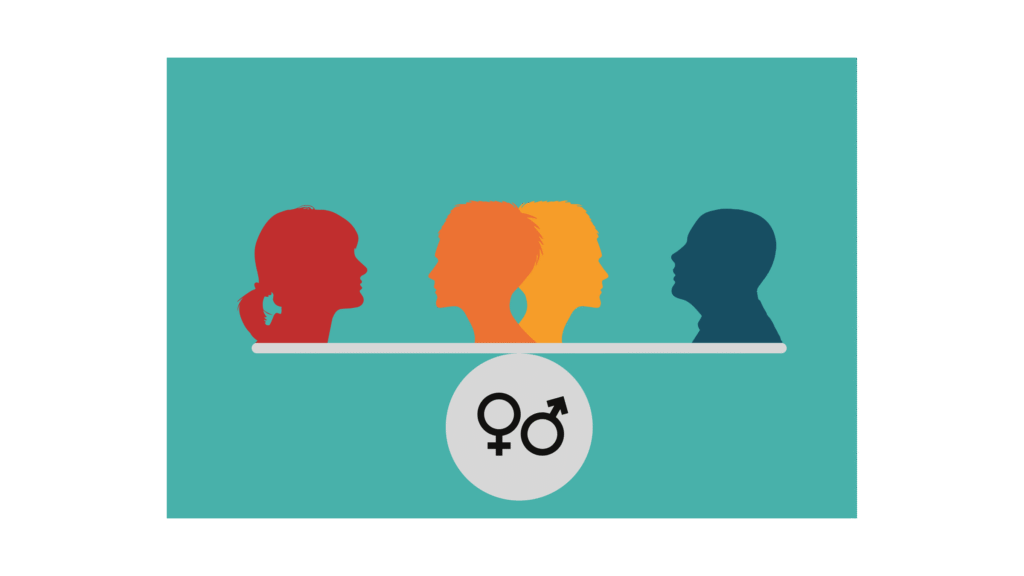
Pada suatu pelatihan, saya sedang memperhatikan sesi tentang Sex vs Gender di tengah para peserta yang sebagian besar merupakan guru. Saat membahas soal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seseorang beropini, “Kalau laki-laki sarapannya pisang, telornya dua ditaruh di sampingnya.” Kita semua tahu ia sedang menggambarkan alat kelamin laki-laki. Dan seperti dugaan, ruangan itu dipenuhi tawa. Candaan itu dianggap lucu, ringan, dan tidak berbahaya. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang merasa perlu mempertanyakan.
Namun bagi saya, momen itu justru membawa ingatan ke masa kecil. Masa ketika ejekan tentang tubuh, bentuk fisik, dan identitas gender menjadi bagian dari keseharian. Candaan-candaan yang dulu kita anggap biasa, ternyata menempel lama: membentuk rasa malu, inferioritas, bahkan kekerasan verbal antar anak. Di titik itu, saya jadi bertanya pada diri sendiri: hari ini, kita sedang menjadi orang dewasa atau justru mengulang perilaku anak-anak yang dulu melukai kita?
Kita tumbuh dengan seperangkat bayangan tentang bagaimana orang dewasa seharusnya bersikap—lebih bijak, lebih sadar, dan mampu menahan diri. Tapi kenyataannya, banyak dari kita membawa serta pola lama tanpa pernah mengujinya kembali. Norma tentang bagaimana laki-laki dan perempuan “seharusnya” berpikir, bercanda, bersikap, dan menilai tubuh orang lain, terus direproduksi, entah dalam balutan humor atau pukulan tangan.
Norma gender memainkan peran besar dalam proses ini. Candaan tentang tubuh laki-laki yang dianggap wajar, maskulinitas yang dilekatkan pada agresi, atau feminitas yang dilekatkan pada kerentanan, membentuk cara kita memandang relasi kuasa. Dari situlah perilaku mengejek, merendahkan, dan bahkan kekerasan menemukan pembenarannya. Ketika orang dewasa menormalisasi bahasa dan sikap yang merendahkan tubuh atau identitas tertentu, pesan itu sampai dengan jelas pada anak-anak: ini boleh, ini lucu, ini bukan masalah.
Dalam konteks kekerasan dan perundungan pada anak dan remaja, kita sering terlalu cepat menunjuk pelaku dan korban yang sama-sama masih muda. Intervensi pun diarahkan hampir sepenuhnya pada remaja: pelatihan, konseling, kampanye, modul. Semua penting. Namun jarang kita bertanya secara jujur: lingkungan seperti apa yang kita ciptakan untuk mereka? Nilai apa yang mereka lihat dipraktikkan oleh orang dewasa di sekitarnya—di rumah, di sekolah, di ruang publik?
Karena mungkin, dalam banyak kasus, yang perlu diintervensi bukan hanya remajanya, tetapi juga kita. Orang dewasa yang tanpa sadar mengamini dan menurunkan norma-norma yang melanggengkan kekerasan. Orang dewasa yang tertawa ketika seharusnya berhenti sejenak dan berpikir. Orang dewasa yang lupa bahwa mereka sedang menjadi contoh.
Di titik inilah, kerja-kerja Sekolah AMAN kami harap menjadi relevan dan mendesak. Upaya menciptakan sekolah yang aman tidak berhenti pada perubahan perilaku siswa, tetapi juga mengajak guru, orang tua, dan komunitas dewasa di sekitarnya untuk merefleksikan peran mereka. Sekolah AMAN mendorong satu kesadaran penting: remaja tidak tumbuh dalam ruang hampa. Jika kita ingin mereka belajar tentang empati, batasan, dan penghormatan, maka orang dewasa di sekitarnya harus terlebih dahulu mempraktikkannya. Karena sekolah yang aman, pada akhirnya, dimulai dari orang dewasa yang berani berhenti tertawa terhadap candaan yang justru mempertebal kekerasan dan mulai bertanggung jawab.



