Oleh: dr. Oka Negara – Ketua Pengurus PKBI Daerah Bali
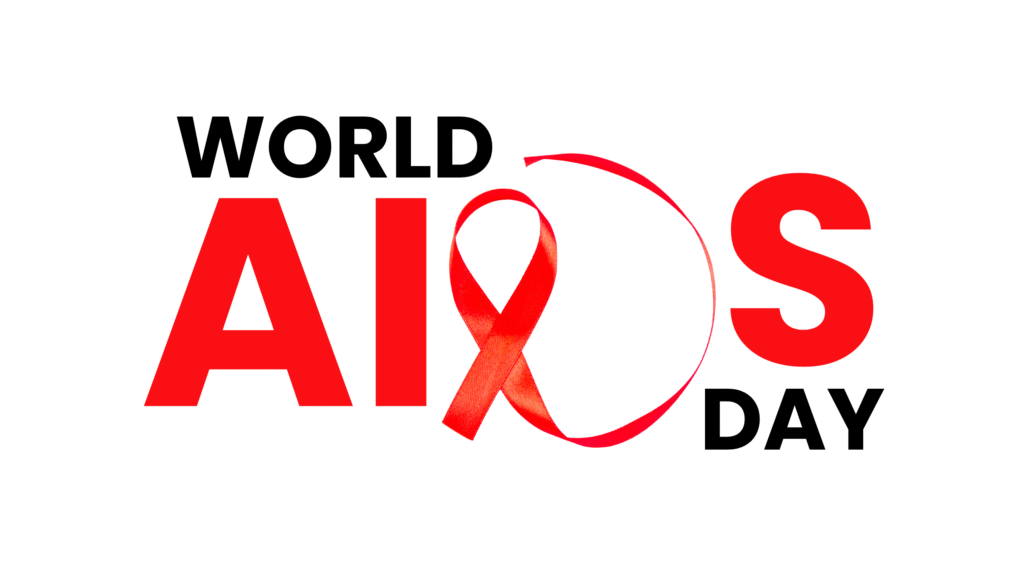
Perubahan sering datang tanpa tanda, tetapi dampaknya terasa di mana-mana. Dalam isu HIV, berbagai perubahan sosial, mobilitas masyarakat, hingga pergeseran pendanaan kesehatan tidak boleh membuat layanan HIV melemah. Sebab, di balik setiap layanan yang bertahan, ada kehidupan yang diperpanjang dan masa depan yang dijaga. Itulah pesan penting Hari AIDS Sedunia 2025 dengan tema “Bersama Hadapi Perubahan, Jaga Layanan HIV.”
Di Bali, pesan ini terasa sangat relevan. Dengan 31.686 estimasi orang hidup dengan HIV, dan lebih dari 91% kasus telah ditemukan, Bali termasuk daerah dengan capaian deteksi yang baik. Tetapi pencapaian ini bukan tanda bahwa perjalanan telah selesai. Tantangan baru justru muncul pada bagaimana memastikan mereka yang sudah ditemukan tetap berada dalam layanan, dan bagaimana layanan itu tetap stabil di tengah perubahan.
Pemahaman dasar tentang HIV juga perlu terus diperkuat. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan hanya menular melalui tiga jalur: hubungan seksual tanpa kondom, paparan darah terkontaminasi, serta penularan dari ibu ke bayi. HIV tidak menular melalui bersalaman, berpelukan, berbagi gelas, atau tinggal serumah. Kesalahpahaman seperti inilah yang melahirkan stigma, dan stigma menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya penanggulangan.
Salah satu pilar penting pengendalian HIV adalah ARV (Antiretroviral), obat yang diminum setiap hari untuk menekan jumlah virus. Ketika jumlah virus dalam tubuh—yang disebut viral load—turun hingga tidak terdeteksi, seseorang tidak dapat menularkan HIV kepada pasangan seksualnya. Prinsip ini dikenal sebagai U=U (Undetectable = Untransmittable), terobosan ilmiah yang mengubah cara dunia memandang HIV. Maka tidak berlebihan jika dikatakan, “ARV bukan hanya obat, tetapi penyelamat hidup.”
Meski begitu, pencegahan tetap penting. Kondom—alat pencegah HIV dan IMS yang efektif hingga 95–98%—masih belum digunakan secara konsisten, terutama oleh kelompok muda dan mereka yang memiliki pasangan tidak tetap. Rasa malu, mitos, dan kurangnya edukasi membuat penggunaan kondom masih rendah.
Perubahan perilaku masyarakat, mobilitas pariwisata, dan gaya hidup digital juga membuat epidemi HIV bergerak cepat. Kasus baru banyak ditemukan pada kelompok usia 20–29 tahun, generasi yang dekat dengan internet tetapi sering terpapar informasi seksual yang tidak akurat. Inilah paradoks pendidikan seksual masa kini: informasi melimpah, literasi rendah.
Di sisi lain, stigma masih menjadi “epidemi bayangan.” Banyak orang menunda tes bukan karena tidak paham risikonya, tetapi karena takut dihakimi. Dalam sesi konseling, tidak jarang seseorang berkata, “Saya takut keluarga malu, Dokter.” Ketakutan seperti ini nyata dan membuat banyak kasus ditemukan sudah dalam kondisi berat.
Namun Bali memiliki kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah: Kader Desa Peduli AIDS, jaringan remaja seperti KSPAN (Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba) dan KMPA (Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS dan Narkoba), serta organisasi masyarakat sipil seperti PKBI Bali, Yakeba, Kerti Praja, Gaya Dewata, dan lainnya yang konsisten menjangkau kelompok paling rentan. Kolaborasi inilah yang membuat Bali lebih tangguh dalam menghadapi epidemi.
Saat ini, tantangan baru muncul dari transisi pendanaan donor internasional ke nasional. Tanpa pendanaan yang kuat, edukasi dan pendampingan bisa melemah. Karena itu, transparansi dan komitmen anggaran menjadi kunci agar penanggulangan HIV tidak mundur.Ending AIDS 2030 bukan sekadar target teknis, tetapi janji moral kita sebagai masyarakat. Jika tes HIV semakin mudah, ARV tetap berkelanjutan, dan stigma terus ditekan, maka Bali berada di jalur yang benar. Sebab seperti dikatakan, “Perjalanan ini panjang, tetapi selama kita berjalan bersama, tidak ada langkah yang sia-sia.



